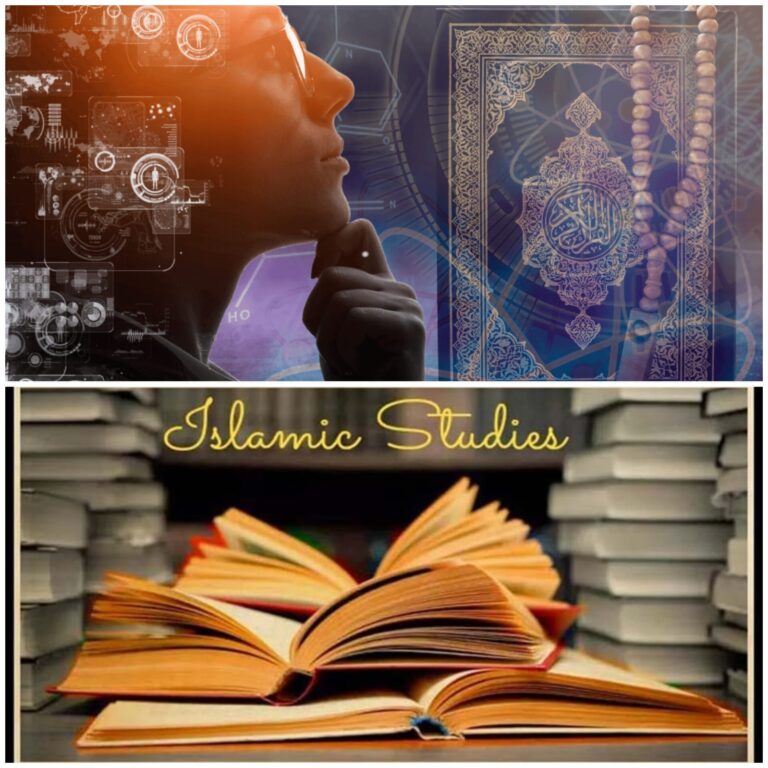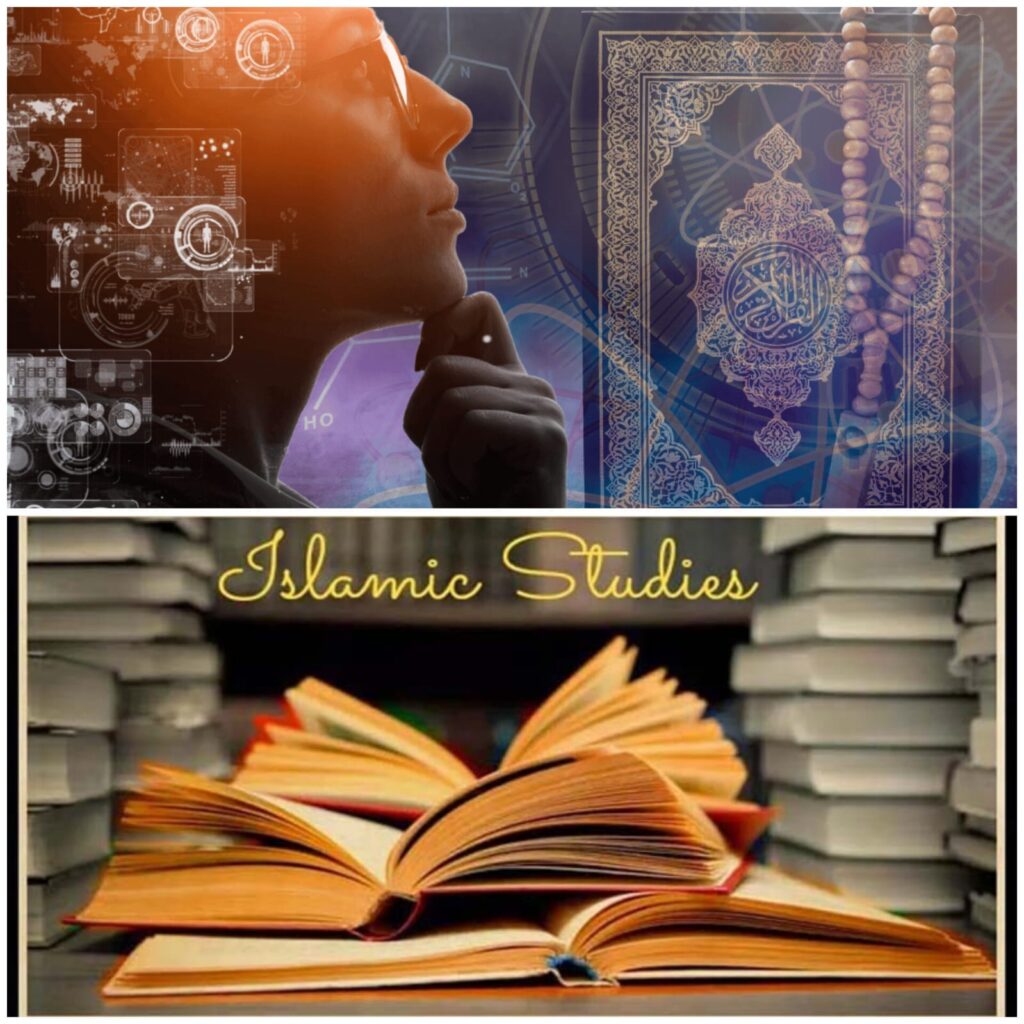
Oleh: Muh. Asyraf Syakur, S.Ag, M.Ag
Banyak pelajar Studi Islam – walaupun tidak semuanya – berusaha mendalami Islam untuk menjadi modernis. Ide semacam ini mencoba meletakkan Islam agar sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan gerak laju ilmu pengetahuan dan teknologi yang kian hari semakin canggih. Kemapanan ilmu pengetahuan dan teknologi diarahkan agar sesuai dengan ajaran Islam klasik yang sedari awal telah terbentuk di era keemasan Islam.
Studi keislaman konvensional seperti Tafsir, Hadis, Aqidah dan Fiqh mengalami interpretasi baru demi berintegrasi dengan ilmu-ilmu sekuler. Bahkan, Filsafat Islam dan Mistisisme Islam pun mengalami hal serupa. Filsafat Islam yang sejak dulu hendak mendudukkan akal agar dapat mencapai “Yang Ilahi” dan menemukan hikmah juga dipaksa tunduk pada kemajuan modern. Begitu juga dengan Mistisisme Islam yang dahulu digunakan untuk membersihkan jiwa agar menjadi suci juga mengalami nasib yang sama.
Integrasi keislaman dan keilmuan sekuler bukan sesuatu yang salah, justru merupakan kebaikan bersama demi menciptakan masyarakat Islam yang lebih maju. Namun, ini bukan berarti ide yang tanpa celah. Banyak lubang yang butuh penambalan ketat, yang jika tidak dilakukan, akan berimbas pada hilangnya jiwa klasik Islam itu sendiri.
Modernisasi Studi Islam saat ini layak disebut “liar”. Keliaran ini berefek pada hilangnya dimensi asli dari ruh klasik Studi Islam. Wacana Tafsir, Hadis, Aqidah dan Fiqh yang tertera dibalik kitab-kitab klasik sering dituduh sebagai jumud, ketinggalan zaman, kaku, bahkan militan. Seakan pendalaman terhadap kitab-kitab klasik adalah hobi masyarakat kuno yang tidak lagi mendapat tempat dalam pikiran dan hati masyarakat modern.
Dimensi klasik Studi Islam, akhirnya, seakan bertempat di altar kuno, sebuah panggung yang terletak di lembah kebodohan yang tak mengenal pencerahan modern. Satu-satunya cara agar manusia tidak jatuh dalam lembah itu adalah memanjat ke arah cahaya modernisasi intelektual, begitu kata mereka.
Padahal, di era klasik, Studi Islam merupakan pencerahan itu sendiri. Model pencerahan itu adalah hasil usaha intelektual masyarakat klasik agar keluar dari jurang kegelapan jahiliyah. Patut diakui bahwa pencerahan di masa itu banyak melibatkan model epistemologi Arab yang menjadikan logika bahasa Arab sebagai landasan keilmuan.
Studi Tafsir, Hadis, Aqidah dan Fiqh sangat kental akan nuansa epistemologi Arab. Ilmu Tafsir, misalnya, selalu beranjak dari logika bahasa Arab yang melekat dalam teks kitab suci Al-Qur’an. Analisis kebahasaan menjadi acuan utama dalam setiap penafsiran. Dalam Ilmu Hadis model periwayatan ala Arab juga sangat mendominasi. Model ini mendapat inspirasi dari tradisi geneologi Arab kuno yang digunakan untuk mencatat silsilah moyang para pendahulu Arab.
Ilmu Aqidah juga tak dapat mengelak dari model epistemologi Arab. Dialektika teologi para mutakallimun selalu berlandasakan pada pengetahuan bahasa Arab yang mendalam. Di sini, logika rasional dan analisis bahasa seakan kawin dalam argumen-argumen pembuktian teologi. Sebelum logika Yunani mendapat tempat dalam tradisi Arab, kaum Mu’tazilah telah lebih dahulu melakukan rasionalisasi bahasa Arab dalam teologi. Artinya, telah terdapat logika khas Arab yang bersamayam dalam bahasa Arab itu sendiri.
Hal ini juga terjadi dalam Ilmu Fiqh. Di masa ketika Ushul Fiqh dibakukan, Ilmu Fiqh mendapat popularitas yang sangat diminati. Banyak fuqaha menyusun teori Ushul Fiqh demi memudahkan dalam menetapkan hukum-hukum syariat. Bahkan, Ushul Fiqh dianggap sebagai puncak dari logika khas Arab itu sendiri. Hanya saja, logika semacam ini mengarah kepada logika hukum. Tidak heran, banyak kaum modernis menyebut Islam sebagai agama hukum, sebuah agama yang hanya melihat penilaian “ketuk palu” semata.
Istilah-istilah seperti halal dan haram, wajib dan sunnah, seakan adalah pakaian mewah yang dikenakan oleh Studi Islam klasik, yang bagi para modernis layak dilepaskan dan diganti dengan desain yang lebih modern. Menanggalkan pakaian klasik berarti mengganti desain kuno. Dan, mengganti desain kuno adalah bukti kemoderenan yang patut mendapat apresiasi.
Filsuf Yunani klasik, Plato, menyatakan bahwa jiwa dan jasad memiliki hubungan erat. Keterkaitan jiwa dan jasad analog dengan hubungan penunggang dan tunggangannya. Sang penunggang adalah jiwa, sedang jasad adalah tunggangan. Tugas penunggang adalah mengendalikan tunggangannya. Jika tunggangan tidak mendapat kendali dari sang penunggang, maka tunggangan akan hilang kendali, dan akan berakibat pada liarnya tunggangan.
Layaknya sang penunggang dan tunggangannya, di mata kaum modernis Studi Islam seperti tunggangan dari modernitas ilmu-ilmu sekuler. Basis keilmuan sekuler yang melandaskan epistemologinya pada logika rasio dan pembuktian empiris mencoba menjadi penunggang yang berkuasa. Kekuasaan semacam ini akan meletakkan Studi Islam di bawah rezim keilmuan sekuler.
Melihat dari analogi ini, akhirnya Studi Islam seperti budak yang harus patuh dan taat di bawah telapak kaki keilmuan sekuler. Basis epistemologi ilmu-ilmu sekuler dijadikan utama untuk membentuk model pencerahan baru. Rasio dan pembuktian empiris memainkan peran penting. Dan, imbas dari semua ini adalah pudarnya dimensi klasik Studi Islam.
Bagi kaum modernis, jika Studi Islam tidak mendapat kendali dari ilmu-ilmu sekuler, maka Studi Islam akan ketinggalan zaman. Ketertinggalan itu akan menjadikan Studi Islam tidak mendapat tempat di mata masyarakat modern. Ditambah lagi pengaruh dari hadirnya positivisme Eropa kian menambah rumit permasalah ini.
Kaum positivisme, terutama pemikiran Auguste Comte, melihat adanya siklus dalam keilmuan manusia. Dimulai dari tahap yang sangat primitif, hingga mencapai puncaknya dalam pengagungan terhadap akal. Di sini, positivisme mengakui bahwa akal adalah basis utama keilmuan, yang darinya manusia terlepas dari belenggu metafisika relijius.
Pemikiran positivisme kian hari semakin menancapkan taringnya dalam internal Studi Islam, namun dengan model yang telah termodifikasi. Ragam modifikasi itu telah membentuk konstelasi berpikir kaum modernis untuk menciptakan teori-teori baru. Hadirnya teori baru menghadirkan iklim yang lebih meriah dalam epistemologi Islam modern. Ditambah dengan lahirnya teori-teori postmodern Eropa, maka kaum modernis juga mengekor untuk mengait secercah harapan darinya.
Pengambilan teori-teori dari luar peradaban Arab, memang, telah terjadi sejak Studi Islam mulai terbentuk. Proses pencarian dan pengambilan keilmuan dari tradisi luar Arab merupakan kegiatan normal, terutama sejak maraknya penerjamahan kitab-kitab dari luar Arab. Penerjamahan ini berakibat pada modifikasi keilmuan.
Namun, para pemikir Arab-Islam klasik juga patut mendapat kritik tajam sebagaimana kaum modernis. Mereka, para pemikir Arab Islam klasik, terlalu menekankan epistemologi Arab terhadap Studi Islam. Hal ini mereka lakukan karena teks suci Al-Qur’an diturunkan dalam bahasa Arab. Sehingga, kultur yang tepat dalam memahami teks suci adalah dari tradisi Arab itu sendiri.
Argumen semacam ini meletakkan Islam terbatas pada proses Arabisasi epistemologi belaka. Iklim intelektual berbasis Arab ini terkesan mengkultuskan budaya Arab sebagai satu-satunya landasan berpikir yang tepat dan terhindar dari segala jenis kesalahan penafsiran. Segala bentuk interpretasi teks suci, akhirnya, seperti budak di hadapan rezim epistemologi Arab.
Meminjam analogi Plato sebelumnya, epistemologi Arab layaknya sang penunggang yang berusaha mengendalikan tunggangannya secara utuh. Oleh karena itu, Studi Islam pun harus selalu mengikuti segala titah dari kultur Arab. Efek dari model berpikir demikian berakibat pada Arabisasi epistemologi yang kian hari semakin terbentuk dalam doktrin-doktrin keislaman. Arab adalah Islam, dan Islam adalah Arab, begitulah kesan dari cara berpikir klasik.
Dua ekosistem dari model integrasi di atas menghasilkan dua kutub pemikiran yang berbeda: integrasi Studi Islam modern dan integrasi Studi Islam klasik. Perbedaan di antara keduanya terletak pada landasan berpikir.
Integrasi Islam modern melihat adanya dikotomi antara dimensi klasik dan modern yang mewarnai dinamika keilmuan Islam. Memadukan dua kutub dimensi ini menjadi gairah utama kaum modernis Islam. Namun, perpaduan yang mereka lakukan seakan mengorbankan ruh klasik dalam Studi Islam. Argumen bahwa Studi Islam harus mengikuti perkembangan zaman adalah bukti otentik bahwa sisi klasik keilmuan Islam harus menjadi pengekor.
Di sisi lain, integrasi Studi Islam klasik yang telah dilakukan berabad-abad lalu hanya mengizinkan epistemologi Arab untuk menafsirkan teks-teks keagamaan dari satu sisi. Artinya, nilai-nilai Islam yang sejak awal diturunkan di tanah Arab harus mendikte dirinya dari budaya Arab itu sendiri. Model semacam ini terkesan meninggalkan jejak bahwa hanya Arab sebagai satu-satunya kultur yang absah.
Singkatnya, integrasi Studi Islam modern melihat adanya oposisi biner antara klasik dan modern. Demi kemajuan Studi Islam agar tidak ketinggalan zaman, maka jalan yang harus ditempuh adalah melihat konteks kebudayaan masyarakat setempat; sesuai dengan dinamika sosial-kebudayan yang mewarnai pola pikir masyarakat modern. Di sini, integrasi Studi Islam modern berangkat dari asas kebudayaan yang telah berlaku sebelumnya. Dengan kata lain, model integrasi ini adalah integrasi berbasis kebudayaan. Dan, basis kebudayan yang dimaksud bersifat plural.
Adapun integrasi Studi Islam klasik, pada dasarnya juga merupakan model integrasi kebudayaan. Hanya saja, basis kebudayaan yang dianutnya berangkat dari satu tradisi semata: tradisi Arab. Tidak heran model semacam ini layak disebut integrasi Studi Islam berbasis kebudayaan yang bersifat tunggal. Ketunggalan ini tidak melihat adanya oposisi biner sebagaimana yang terjadi dalam cara berpikir kaum modernis, tapi hanya melirik Studi Islam sebagaimana dia diturunkan pada awal kemunculannya di tanah Arab.
Akhirnya, dua ekosistem integrasi keilmuan ini dapat disimpulkan sebagai integrasi berbasis budaya, namun keduanya memiliki perbedaan:
- Integrasi modern: budaya plural
- Integrasi klasik: budaya tunggal
Plurariltas dan ketunggalan yang dianut masing-masing integrasi keilmuan Islam ini mewarnai dinamika keilmuan Islam hingga sekarang. Pluraritas integrasi modern banyak diadopsi masyarakat universitas dalam ruang-ruang akademik. Sedang, ketunggalan integrasi klasik masih menjadi panutan utama dalam kurikulum-kurikulum pesantren.
Perbedaan di antara keduanya menciptakan ruang interpretasi berbeda. Para cerdik pandai akademisi cenderung mengarah kepada liberalisasi penafsiran terhadap teks-teks keagamaan. Oleh sebab itu, masyarakat universitas sering dicap sebagai kaum yang senang mengotak-atik agama. Sedang, alumnus pesantren sering memperoleh hujatan sebagai kaum terbelakang yang hanya bergelut dalam kitab-kitab kuno.
Jurang pemisah di antara keduanya sering menuai polemik dalam masyarakat Islam, khususnya ketika isu-isu penafsiran mencuat ke permukaan. Dalam menengahi dua iklim di atas, para pemikir Islam memberi solusi akurat. Naquib al-Attas menawarkan “Islamisasi Ilmu”, namun Kuntowijoyo menolak tawaran ini dengan mengajukan “Ilmuisasi Islam”.
Secara praktis, kedua tawaran ini terkesan memberi solusi jitu. Namun, terdapat kejanggalan di antara keduanya. Islamisasi Ilmu dinilai seakan melihat seluruh keilmuan sebagai non-Islam, sehingga harus melakukan Islamisasi Ilmu. Sedang, Ilmuisasi Islam cenderung menyodorkan argumen bahwa Islam tidak memiliki basis keilmuan di tengah maraknya ilmu-ilmu sekuler, sehingga tawaran semacam ini hanya mengarah kepada utopia.
Tulisan ini hendak menyatakan bahwa integrasi Studi Islam sejak dahulu hingga sekarang senantiasa berangkat dari cara manusia menafsirkan teks-teks keagamaan. Relasi antara penafsir dan objek yang ditafsirkan itulah yang selama ini mewarnai dinamika keilmuan Islam. Artinya, apa yang dimaksud sebagai integrasi Studi Islam adalah menghadirkan nilai-nilai keislaman berdasarkan budaya dari sang penafsir. Corak berpikir penafsir tidak akan pernah lepas dari konteks kebudayaan dimana mereka hidup.
Perbedaan budaya mengakibatkan keilmuan Islam semakin melimpah. Menghadirkan keragaman juga turut membawa Studi Islam kepada kejamakan interpretasi. Dan, kejamakan inilah yang sering tertancap dalam setiap alur sejarah keilmuan Islam. Di setiap masa, bantahan demi bantahan terhadap pemikiran sebelumnya menghasilkan dialektika yang kian hari semakin memperuncing masalah. Segala jenis solusi diajukan. Seluruh bantahan akan mendapat serangan balik oleh para pemikir setelahnya. Begitulah yang terjadi secara terus menerus.
Tulisan ini juga tidak hendak menyatakan bahwa hanya ada satu sistem yang harus mendominasi. Ketunggalan dalam interpretasi merupakan sesuatu yang patut dihindari, karena akan berakibat pada sifat monoton dan kaku dalam keilmuan Islam. Kekakuan akan berefek pada keangkuhan. Menolak keragaman berarti menolak segala jenis warna, dan hal semacam ini serupa dengan kebutaan. Oleh sebab itu, “Menjinakkan Integrasi Studi Islam” adalah penjinakan dalam arti mengendalikan diri. Menjinakkan diri bermaksud mengarahkan sang subjek agar mengetahui bahwa diri berada dalam lingkaran keragaman. Berada ditengah keragaman membawa pada kesadaran bahwa segala jenis integrasi telah menciptakan pertentangan di antar jenis kubu yang berbeda. Dengan kata lain, penjinakan terhadap integrasi Studi Islam yang dimaksud adalah menjinakkan diri itu sendiri. (*)